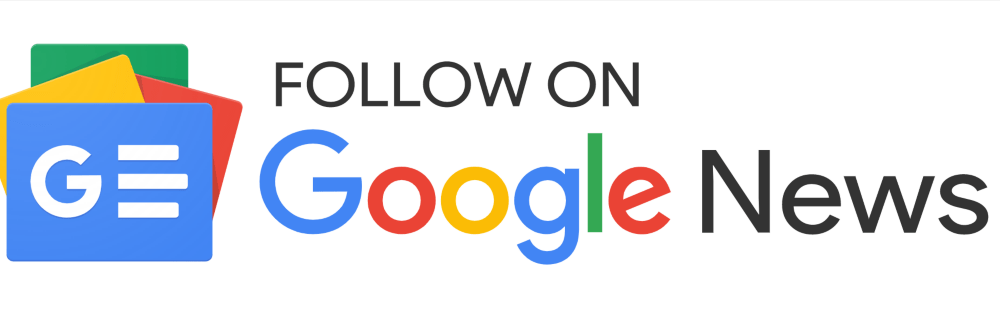Oleh: Komaruddin Hidayat (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Sebuah tulisan oleh Laura Hazard Owen (Mei 2018), diangkat dari Schizophrenia International Research Fonference, membahas seputar berita bohong (fake news). Menurutnya, terdapat tiga kategori atau kelompok sosial yang mudah percaya pada berita bohong, tanpa sikap kritis. Pertama, orang yang suka melamun (delusional), memikirkan hal-hal yang serba ideal, utopis, namun tidak realistik. Kedua, mereka yang berpikir dogmatik, dan, ketiga, orang yang religius-fundamentalis.
Kita boleh percaya dan ragu atas kesimpulan itu, karena tidak tahu secara persis metodologi yang digunakan serta siapa saja obyek yang diteliti. Namun secara common sense, sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk memahami hasil penelitian itu. Pertama, orang yang delusional, yang senang berpikir utopis dan mudah percaya pada hal-hal yang gaib, pasti akan mudah percaya pada berita takhayul dan dongeng-dongeng yang sejalan dengan lamunannya. Dia tidak bisa membedakan antara realitas dan fantasi, antara informasi palsu dan informasi yang sahih.
Kedua, orang yang berpikir dogmatik. Biasanya enggan menerima pemikiran yang tidak sejalan dengan keyakinannya yang telah mengkristal. Mereka enggan berdialog dan berdiskusi secara kritis-ilmiah, karena pikirannya sudah tertutup, ekslusif, takut keyakinannya akan terganggu serta goyah jika ketemu pikiran lain yang lebih rasional dan menawarkan cara pandang baru. Kalau berita datang, sekalipun palsu, tidak keberatan menerimanya selama tidak bertabrakan dengan sikapnya. Di situ sikap emosional lebih menonjol ketimbang sikap rasional. Pilihan “like and dislike” lebih menonjol ketimbang “right and wrong”.
Yang membuat saya penasaran adalah riset itu menyimpulkan bahwa sikap orang yang religius-fundamentalis mudah percaya pada “fake news”. Apakah konsep “fake news” itu juga tidak ada penjelasan dan contohnya. Namun ketika saya mengamati perilaku orang beragama yang tergolong fanatik, mereka memang tidak menyukai diskusi soal agama. Mereka telah memikiki keyakinan keagamaan yang sudah final. Di sana tak diperlukan diskusi, tapi mesti diimani dan dilaksanakan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka yakini itu awalnya adalah produk penafsiran yang kemudian dibakukan dan disakralkan. Dengan kata lain, telah terjadi sakralisasi dan absolutisasi pemahaman dan penafsiran atas ajaran agamanya.
Hari-hari ini “fake news” dan “hoax” bertaburan di jagad medsos, bertemu antara pilihan politik dan keyakinan agama. Apa yang ditulis oleh Laura Hazard Owen seakan memperoleh pembenaran empiris. Ketika sekelompok masyarakat menempatkan pilihan politik menjadi semacam dogma yang mengeras, kemudian diberi legitimasi yang diaggap sakral oleh ajaran agama, maka berita dan analisis rasional apapun seputar politik yang isinya berbeda dengan pilihannya langsung ditolak. Sebakiknya, meskipun berita “hoax” jika isinya memperkuat pilihannya maka tidak segan-segan malah ikut menyebarkannya. Bahkan ketika seorang tokoh bicara soal politik, yang pertama ditanyakan adalah “tokoh” itu apa pilihan politiknya, bukan isi dan argumennya. Kalau kebetulan sama maka pantas didengarkan, meskipun mungkin kurang bermutu. Sebaliknya, kalau berseberangan, tak perlu didengarkan, meskipun bisa jadi isinya berkualitas. Yang tidak enak adalah perikaku di atas bagian dari kondisi kejiwaan yang tidak sehat, yang dalam penelitian itu masuk kategori schizophrenia. (*)

 Serba-Serbi7 hari ago
Serba-Serbi7 hari agoKalender Februari 2026 Lengkap

 Serba-Serbi6 hari ago
Serba-Serbi6 hari agoKalender 2026 Pdf Free Download

 Nasional7 hari ago
Nasional7 hari agoBandara Internasional Banyuwangi Perkuat Peran sebagai Bandara Ramah Anak dan Ramah Lingkungan

 Serba-Serbi7 hari ago
Serba-Serbi7 hari agoAwal Puasa Ramadhan 1447 H Muhammadiyah Jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026

 Banten6 hari ago
Banten6 hari agoJajaran Pengurus Bank Banten RUPS Luar Biasa Tahun 2026

 Banten6 hari ago
Banten6 hari agoKomisi V DPRD Banten dan Dindik Bahas Program Sekolah Gratis di APBD 2026

 Banten6 hari ago
Banten6 hari agoBank Banten Kelola Penuh Keuangan BLUD RSUD Balaraja

 Bisnis6 hari ago
Bisnis6 hari agoMasuk Indonesia, Haier Siapkan Produk Premium dan Strategi eCommerce Agresif