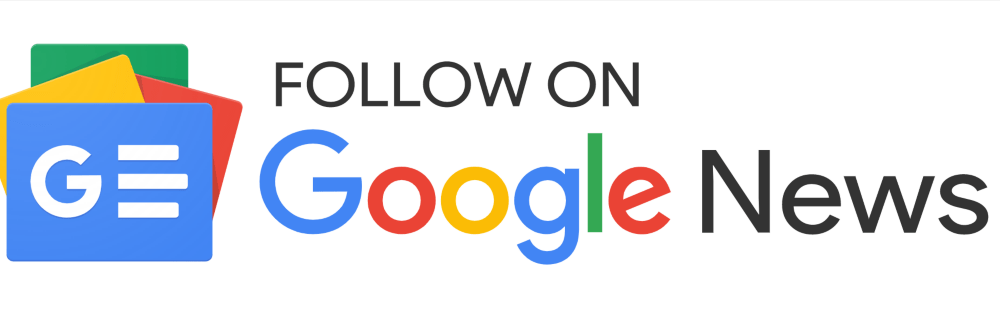Opini
Ketika Rumah Pemimpin Negara Tak Lagi Sakral

Oleh: Fendry Akhyar Ariefuzzaman, S.Sos
Kabar tentang diculiknya Nicolás Maduro dan istrinya dari kediaman mereka oleh Amerika Serikat—apa pun versi dan klaim yang beredar—seketika mengingatkan dunia pada operasi senyap lain yang pernah menghebohkan jagat internasional. Ingatan publik melompat ke era Barack Obama, ketika tokoh teroris paling diburu di dunia, Osama bin Laden, ditangkap lalu dibunuh dalam operasi rahasia, dan jasadnya kemudian dilarung di Samudra Hindia.
Dua peristiwa ini, meski konteksnya berbeda, memperlihatkan satu hal yang sama: supremasi Amerika Serikat dalam kekuatan militer dan operasi senyap. Sebuah kemampuan yang bukan hanya menunjukkan kecanggihan teknologi dan intelijen, tetapi juga memperlihatkan tingkat kepercayaan diri—atau mungkin jumawa—yang sangat tinggi. Sebab operasi-operasi itu dilakukan dengan menembus wilayah negara berdaulat, yang sejatinya dilindungi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dari satu sisi, tindakan semacam itu jelas merupakan agresi. Dalam kasus Bin Laden, sebagian orang mungkin berargumen bahwa operasi tersebut “berhasil” karena mampu melumpuhkan jaringan Al-Qaeda. Namun tetap saja, masuknya pasukan Amerika ke wilayah Pakistan secara senyap adalah tamparan keras bagi kedaulatan negara itu. Perdebatan pun muncul dan tak pernah benar-benar selesai: apakah sebuah negara berhak melakukan operasi sepihak di wilayah negara lain yang berdaulat, dengan alasan apa pun?
Pertanyaan yang sama—bahkan mungkin lebih keras—muncul dalam konteks penculikan Maduro. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ketika dunia menyaksikan peristiwa global secara langsung dan nyaris tanpa filter, tindakan semacam itu tampil telanjang di hadapan publik internasional. Apakah tindakan tersebut bisa dibenarkan? Atau justru menjadi preseden berbahaya?
Jika para pemimpin dunia memilih diam, maka diam itu sendiri adalah pesan. Pesan bahwa tindakan Amerika dianggap wajar, dimaklumi, atau setidaknya bisa diterima. Konsekuensinya jelas: negara-negara lain akan belajar dari situasi itu. Mereka akan berlomba-lomba memperkuat senjata, meningkatkan anggaran militer, dan menyiapkan pengamanan superketat bagi presiden serta keluarga pemimpinnya.
Lebih berbahaya lagi, tindakan semacam ini membuka peluang bagi negara kuat lain untuk menyerang negara yang lebih lemah dengan alasan-alasan subjektif versi mereka sendiri. Dan dunia—sekali lagi—mungkin hanya menonton. Kalaupun bersuara, suaranya terdengar lirih, lemah, nyaris tak berdaya, seolah berkata: asal jangan kami yang diserang berikutnya.
Sejarah menunjukkan bahwa menyerang atau menyasar kediaman pemimpin negara bukan hal baru, baik dalam kondisi perang maupun damai. Belum lama ini, dunia dikejutkan oleh serangan drone ke kediaman Vladimir Putin. Fakta bahwa rumah pemimpin negara adidaya pun bisa menjadi target, mengirimkan pesan yang sangat kuat: tak ada lagi ruang yang benar-benar sakral.
Secara geopolitik, serangan semacam itu jelas bukan kerjaan iseng. Ia sangat mungkin merupakan bagian dari operasi psikologis (psychological operation atau psy-ops). Tujuannya bukan semata kerusakan fisik, melainkan mengguncang rasa aman. Pesannya sederhana namun tajam: “Kami bisa menyentuhmu.”
Di sisi lain, serangan juga bisa dimaksudkan sebagai provokasi untuk meningkatkan ketegangan dan eskalasi konflik. Sebuah insiden dapat dimanfaatkan—atau dibingkai—untuk membenarkan langkah balasan yang lebih keras. Dalam politik global, narasi sering kali sama pentingnya dengan fakta, bahkan kadang lebih menentukan arah sejarah.
Menyerang simbol pribadi seorang pemimpin di tengah konflik dunia adalah tanda bahwa garis merah makin kabur. Perang hari ini tidak selalu dimulai dengan tank dan pasukan infanteri, melainkan dengan pesan, ketakutan, dan persepsi. Dunia pun sedang diuji: apakah konflik akan dikelola dengan akal sehat, atau justru dibiarkan naik kelas oleh kesombongan, ego, dendam, dan adu kekuatan.
Jika pola penyerangan terhadap simbol negara ini menjadi tren, dampaknya akan panjang. Setiap negara akan semakin memusatkan belanja militernya pada pengamanan simbol-simbol kekuasaan: keluarga pemimpin, istana, pusat pemerintahan, ibu kota. Sejarah menunjukkan, kondisi semacam ini sering melahirkan pemimpin yang hidup dalam paranoia—tak tersentuh, tertutup, dan memandang siapa pun, bahkan rakyatnya sendiri, sebagai potensi ancaman.
Karena itu, dunia tidak boleh diam. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bergerak. Regulasi internasional perlu diperbaiki, dan Dewan Keamanan PBB sudah saatnya direvisi. Dunia telah berubah cepat, sementara banyak aturan global masih merupakan produk zaman perang lama.
Pada akhirnya, satu harapan yang tersisa dan paling mendasar tetap sama: dunia harus damai. Perang seharusnya menjadi masa lalu. Manusia berhak hidup aman, adil, dan sejahtera—tanpa harus terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan siapa yang akan diserang berikutnya.

 Serba-Serbi4 hari ago
Serba-Serbi4 hari agoKalender Februari 2026 Lengkap

 Serba-Serbi4 hari ago
Serba-Serbi4 hari agoKalender 2026 Pdf Free Download

 Nasional5 hari ago
Nasional5 hari agoBandara Internasional Banyuwangi Perkuat Peran sebagai Bandara Ramah Anak dan Ramah Lingkungan

 Serba-Serbi4 hari ago
Serba-Serbi4 hari agoAwal Puasa Ramadhan 1447 H Muhammadiyah Jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026

 Pendidikan7 hari ago
Pendidikan7 hari agoDaftar Homeschooling Kini Semakin Mudah di Pride Homeschooling Ciputat

 Banten4 hari ago
Banten4 hari agoJajaran Pengurus Bank Banten RUPS Luar Biasa Tahun 2026

 Banten4 hari ago
Banten4 hari agoKomisi V DPRD Banten dan Dindik Bahas Program Sekolah Gratis di APBD 2026

 Jabodetabek6 hari ago
Jabodetabek6 hari agoJakarta Madrasah Award 2026, MI dan MA Pembangunan UIN Jakarta Raih Penghargaan Bergengsi